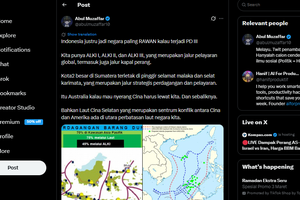Ketika Wirid Menggema, Sumpah Tapanuli Mengikat Nurani

KOMPAS.com - Di tepi sungai yang masih membawa sisa murka alam, ratusan warga duduk bersila di atas terpal lusuh.
Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk tokoh Tapanuli, sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rahmat Hidayat Pulungan, hadir di tengah para korban.
Lumpur belum sepenuhnya mengering, kayu-kayu gelondongan masih berserakkan, dan udara lembab menyimpan bau duka.
Namun Kamis siang itu, di Desa Hutaraja, Kecamatan Muara Batangtoru, Tapanuli Selatan, ada sesuatu yang perlahan dibangkitkan kembali, ingatan, nurani, dan kesadaran akan peradaban.
Doa dan wirid menggema lebih dulu. Lafal-lafal itu dilantunkan pelan, seolah memberi ruang bagi setiap orang untuk menata kembali batin yang tercerai-berai oleh bencana.
Wirid, Sumpah, dan Ingatan yang Dipanggil Kembali
Wirid bukan sekadar pembuka acara. Ia menjadi jeda reflektif, sebuah perenungan tentang makna hidup.
“Wirid berdoa itu kan sebuah perenungan, sebagai pertanyaan kita ini hidup tujuannya apa sih? Kita hidup ini untuk siapa?” ujar Rahmat.
Dari perenungan itulah sumpah kemudian dihadirkan. Bukan deklarasi, bukan pula pernyataan sikap. Rahmat memilih sumpah karena ia percaya hanya ikrar sakral yang mampu mengikat manusia melampaui kepentingan sesaat.
“Saya perhatikan selama 43 hari di Tapanuli ini, yang salah itu bukan cuma pemerintah pusat, pemerintah daerah salah, pejabat salah, aparat salah, kepala daerah salah, masyarakat juga salah karena membiarkan itu semua.” katanya.
Baca juga: Wasekjen PBNU Soroti Akar Banjir Bandang Tapanuli, Pemerintah Diminta Bekerja Paralel
Dalam situasi semacam itu, menurut Rahmat, kata-kata formal mudah diucapkan dan mudah dilupakan. Karena itu ia merasa perlu “memaksa” semua pihak untuk mengikat diri pada janji yang lebih dalam.
“Saya mikir, gimana ya cara menyelesaikan masalah ini tapi mengunci semuanya, nah saya harus memaksa mereka bersumpah. Karena sumpah itu sesuatu yang sangat sakral dengan langit dan bumi.” ungkpanya.
Bagi masyarakat Tapanuli, sumpah tidak dipandang sekadar simbol, melainkan sebagai fondasi etik dan spiritual yang berfungsi sebagai perjanjian suci antara manusia dengan Yang Maha Kuasa serta para leluhur, sekaligus diyakini mampu mengaktifkan kembali sisi terdalam manusia, seperti hati nurani, akal sehat, dan kesadaran transenden, sebagai penuntun dalam menjalani kehidupan.
Pada hakikatnya manusia punya hal-hal yang sangat dalam dan abstrak. Di situlah ada nurani, ada akal sehat, serta ada hubungan dengan Tuhan dan leluhurnya.
Di hadapan sungai yang menjadi saksi banjir bandang, sumpah Tapanuli pun diikrarkan. Laki-laki, perempuan, pemuda hingga anak-anak berkumpul bersama, melafalkan janji dalam bahasa ibu dan bahasa Indonesia.
Kalimatnya sederhana, tetapi mengandung beban sejarah dan masa depan, menjaga tanah leluhur, memajukan sumber daya manusia, dan memastikan keberlanjutan Tapanuli bagi generasi mendatang.
Rahmat menegaskan bahwa sumpah tersebut harus terus dihidupkan dan dijaga keberlangsungannya, karena sumpah diyakini akan selalu melekat dalam ingatan kolektif masyarakat dan dihayati secara berulang dalam kehidupan sehari-hari, baik dari hari ke hari maupun dari waktu ke waktu.
“Kalau nggak dibuat sumpah, nanti mereka lupa. Waktu di bawah mereka ingat, begitu punya jabatan, mereka lupa.” tegasnya.
Baca juga: Usai Wirid, Korban Banjir Bandang Ikrarkan Sumpah Tapanuli
Dalam pandangannya, bencana besar yang terjadi hari ini adalah momentum untuk mengembalikan ingatan kolektif. Bencana-bencana terbesar selama 100 tahun ini harus menjadi pengingat masa lalu dan pijakan membangun masa depan.
Dalam adat Tapanuli dan banyak wilayah Sumatra, sumpah dipandang sebagai ikatan paling sakral. Melanggarnya diyakini membawa konsekuensi.
“Sumpah itu paling sakral, kalau dilanggar, dia akan kena karma dan musibah terus. Itu kekuatan etik dan spiritual yang selama ini jadi pegangan orang-orang Tapanuli.” kata Rahmat.
Karena itu, ia mendorong agar sumpah tidak berhenti sebagai seremoni semata, melainkan terus digaungkan, dibaca, dan dihayati secara kolektif oleh seluruh elemen masyarakat Tapanuli dari utara, tengah, selatan, hingga timur, sebagai pedoman moral bersama dalam menjaga tanah dan peradaban mereka.
Ketika Tanah Emas Menuntut Kesadaran Peradaban
Bagi Rahmat, apa yang terjadi di Tapanuli bukan sekadar krisis lingkungan, melainkan krisis peradaban.
“Ini bukan cuma kesadaran ekologis, ini kesadaran peradaban,” tegasnya.
Ia menyinggung bahwa kekayaan yang dikumpulkan melalui cara-cara yang keliru pada akhirnya dapat lenyap seketika, menjadi pelajaran pahit bahwa harta yang tidak dibangun di atas etika dan tanggung jawab hanya akan berujung pada kehancuran.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa sikap masa bodoh terhadap kerusakan lingkungan membuat semua orang menjadi korban.
“Dulu kamu nggak melakukan kesalahan, tapi kamu membiarkan orang berbuat salah. Ketika bencana datang, kamu kena juga.”
Tapanuli, dalam gambaran Rahmat, adalah “tanah emas”. Kaya potensi, tetapi sarat risiko.
“Tapanuli itu surga emas di Sumatra, tapi secara geologis ada lempengan, ada gunung aktif, ada sungai-sungai besar. Godaannya besar.” kata Rahmat.
Dalam metaforanya, Tuhan memberi emas sekaligus alarm bencana. Risiko yang telah dihitung secara pasti. Di sinilah ilmu dan kecerdasan diuji, apakah dipakai untuk menahan godaan atau justru untuk merusak.
Baca juga: Wasekjen PBNU Gagas Taman Monumen Bencana Antropogenik di Tapanuli
Rahmat mengingat kembali kehidupan orang-orang tua dahulu yang dijalaninya secara seimbang, di mana mereka menghabiskan waktu dari pagi hingga sore untuk berkebun, lalu kembali untuk beribadah, makan, dan beristirahat, tanpa dorongan untuk mengejar kekayaan secara berlebihan. Ironisnya keseimbangan tersebut mulai rusak ketika materialisme masuk.
“Kalau nggak kaya, nggak dihormati. Kalau nggak jadi pejabat, nggak dihormati. Itu racun yang merusak budaya.”
Menjelang akhir acara, nama-nama besar Tapanuli dipanggil, Adam Malik, Ahmad Haris Nasution, Syekh Mustofa Nasution, Lafran Pane, Akbar Tandjung, hingga M Panggabean.
Penyebutan itu bukan sekadar penghormatan, melainkan pengingat bahwa Tapanuli pernah melahirkan peradaban besar yang berpijak pada etika, ilmu, dan keseimbangan.
Di atas tanah yang masih basah oleh luka, sumpah itu menggema sebagai penanda. Bahwa Tapanuli tidak hanya berduka, tetapi juga berjanji.
Bahwa dari puing bencana, kesadaran bisa tumbuh kembali dengan sumpah sebagai jangkar ingatan dan dengan peradaban sebagai tujuan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang-
![]() PBNU Gelar Doa dan Ajak Masyarakat Bersatu Bantu Penyintas Bencana
PBNU Gelar Doa dan Ajak Masyarakat Bersatu Bantu Penyintas Bencana -
![]() PBNU Gelar Doa untuk Negeri "Satu NU Satu Bangsa" untuk Bantu Penyintas Bencana
PBNU Gelar Doa untuk Negeri "Satu NU Satu Bangsa" untuk Bantu Penyintas Bencana -
![]() Wasekjen PBNU: Pilkada lewat DPRD Bukan Solusi, Tapi Bencana Politik
Wasekjen PBNU: Pilkada lewat DPRD Bukan Solusi, Tapi Bencana Politik -
![]() Wasekjen PBNU Gagas Taman Monumen Bencana Antropogenik di Tapanuli
Wasekjen PBNU Gagas Taman Monumen Bencana Antropogenik di Tapanuli -
![]() Usai Wirid, Korban Banjir Bandang Ikrarkan Sumpah Tapanuli
Usai Wirid, Korban Banjir Bandang Ikrarkan Sumpah Tapanuli -
![]() Wasekjen PBNU Soroti Akar Banjir Bandang Tapanuli, Pemerintah Diminta Bekerja Paralel
Wasekjen PBNU Soroti Akar Banjir Bandang Tapanuli, Pemerintah Diminta Bekerja Paralel