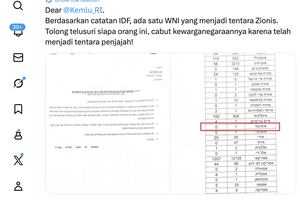Perjanjian Hudaibiyah, Perjanjian Damai yang Mengubah Sejarah Islam

KOMPAS.com - Perjanjian Hudaibiyah merupakan salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah awal Islam.
Meski pada awalnya tampak merugikan umat Islam, kesepakatan ini justru membuka jalan bagi kemenangan dakwah Nabi Muhammad SAW secara lebih luas dan berjangka panjang.
Peristiwa ini terjadi pada tahun keenam Hijriah, ketika umat Islam belum berada pada posisi politik dan militer yang sepenuhnya kuat.
Nabi Muhammad SAW bersama sekitar 1.400 sahabat berangkat dari Madinah menuju Makkah dengan niat menunaikan umrah.
Mereka mengenakan pakaian ihram dan tidak membawa perlengkapan perang, sebagai isyarat bahwa kedatangan mereka bersifat damai.
Namun, kaum Quraisy menilai kehadiran rombongan ini sebagai ancaman politik dan simbolik. Mereka khawatir wibawa Makkah runtuh jika kaum Muslimin memasuki kota tanpa perlawanan.
Baca juga: Piagam Madinah, Landasan Toleransi dan Persatuan Umat Islam
Ketegangan di Perbatasan Makkah
Rombongan Nabi akhirnya tertahan di wilayah Hudaibiyah, sekitar 20 kilometer dari Makkah. Di tempat inilah negosiasi panjang berlangsung.
Utusan demi utusan dikirimkan oleh kedua belah pihak untuk meredakan ketegangan. Salah satu momen paling menegangkan terjadi ketika Utsman bin Affan diutus Nabi untuk berunding ke Makkah, tetapi lama tidak kembali.
Isu bahwa Utsman dibunuh sempat beredar dan memicu baiat setia para sahabat kepada Nabi yang dikenal sebagai Baiat Ridwan.
Ketegangan itu akhirnya mereda ketika Quraisy mengirim Suhail bin Amr sebagai juru runding. Kehadirannya menjadi sinyal bahwa kesepakatan damai akan dicapai.
Isi Perjanjian yang Diperdebatkan
Perjanjian Hudaibiyah memuat beberapa poin utama. Umat Islam diminta kembali ke Madinah dan baru boleh melaksanakan umrah pada tahun berikutnya.
Gencatan senjata disepakati selama sepuluh tahun. Jika ada penduduk Makkah yang masuk Islam dan hijrah ke Madinah tanpa izin walinya, ia harus dikembalikan. Sebaliknya, jika ada Muslim Madinah yang kembali ke Quraisy, ia tidak wajib dikembalikan.
Bagi banyak sahabat, terutama Umar bin Khattab, isi perjanjian ini terasa tidak adil. Mereka mempertanyakan mengapa umat Islam harus mengalah, padahal berada di pihak yang benar.
Namun Nabi Muhammad SAW menerimanya dengan ketenangan dan keyakinan bahwa keputusan ini mengandung hikmah besar.
Baca juga: Kisah Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah
Kemenangan Tanpa Pedang
Waktu membuktikan kebijaksanaan Nabi. Masa damai membuka ruang dakwah yang sebelumnya tertutup oleh konflik bersenjata.
Interaksi antara Muslim dan non-Muslim meningkat dan ajaran Islam menyebar lebih cepat. Dalam dua tahun setelah perjanjian ini, jumlah orang yang masuk Islam melampaui seluruh periode sebelumnya.
Al-Qur’an bahkan menyebut perjanjian ini sebagai “kemenangan yang nyata” (QS. Al-Fath: 1). Kemenangan tersebut bukan dalam bentuk penaklukan wilayah, melainkan pengakuan politik dan legitimasi sosial terhadap komunitas Muslim.
Jalan Menuju Fathu Makkah
Dikutip dari buku Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisyam, perjanjian Hudaibiyah menjadi landasan bagi peristiwa besar berikutnya, yakni penaklukan Makkah.
Ketika Quraisy melanggar perjanjian dengan menyerang sekutu kaum Muslimin, Nabi memiliki dasar moral dan politik untuk bertindak. Fathu Makkah pun terjadi hampir tanpa pertumpahan darah.
Baca juga: Asal Usul Suku Quraisy, Penguasa Mekkah di Zaman Nabi Muhammad SAW
Pelajaran Strategis dari Hudaibiyah
Perjanjian Hudaibiyah mengajarkan bahwa kemenangan dalam peradaban tidak selalu diraih melalui konfrontasi.
Kesabaran, diplomasi, dan visi jangka panjang sering kali lebih menentukan. Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa mengalah secara taktis bukan berarti kalah secara strategis.
Dalam konteks sejarah Islam, Hudaibiyah menjadi contoh bagaimana kebijakan damai dapat menjadi alat transformasi sosial dan peradaban yang jauh lebih kuat daripada pedang.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang-
![]() Asal Usul Suku Quraisy, Penguasa Mekkah di Zaman Nabi Muhammad SAW
Asal Usul Suku Quraisy, Penguasa Mekkah di Zaman Nabi Muhammad SAW -
![]() Aisyah: Istri Nabi Muhammad SAW Paling Banyak Meriwayatkan Hadits
Aisyah: Istri Nabi Muhammad SAW Paling Banyak Meriwayatkan Hadits -
![]() Kisah Nabi Muhammad SAW Lupa Mengucapkan Insya Allah
Kisah Nabi Muhammad SAW Lupa Mengucapkan Insya Allah -
![]() Sirah Nabawiyah: Kisah Hidup Nabi Muhammad SAW dari Lahir hingga Wafat
Sirah Nabawiyah: Kisah Hidup Nabi Muhammad SAW dari Lahir hingga Wafat -
![]() Kisah Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah
Kisah Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah -
![]() Piagam Madinah, Landasan Toleransi dan Persatuan Umat Islam
Piagam Madinah, Landasan Toleransi dan Persatuan Umat Islam -
![]() Nabi Muhammad dan Jalan Panjang Meraih Gelar Al-Amin
Nabi Muhammad dan Jalan Panjang Meraih Gelar Al-Amin