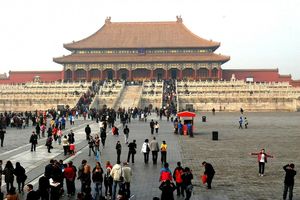Rahasia Pesantren Buntet Bertahan 275 Tahun: Manuskrip, Sorogan, dan Bandongan

CIREBON, KOMPAS.com - Di Desa Mertapada Kulon, Cirebon, berdiri salah satu pusat keilmuan Islam tertua di Jawa Barat: Pesantren Buntet.
Didirikan pada 1750 oleh ulama kharismatik Mbah Muqoyyim (Muqoyyim bin Abdul Hadi), kawasan ini bukan sekadar pondok, melainkan kampung ilmu yang hidup—dari lisan ke tulisan, dari kitab ke praktik.
Tim Kompas.com pada Jumat, 5 Desember 2026 sempat berkunjung ke Pesantren Buntet.
Saat memasuki gerbang bertuliskan “Pondok Buntet Pesantren”, Tim Kompas.com seperti menapak jejak waktu.
Baca juga: Muhaimin Dorong Sarjana NU Perkuat Transformasi Pesantren
Di sinilah tradisi keilmuan yang berusia lebih tua dari republik tetap dirawat, bukan sebagai nostalgia, melainkan sebagai kurikulum yang masih diajarkan hari ini.
43 Manuskrip: Jejak Ilmu yang Diikat Santri
 Nyai Mamay menunjukkan salah satu manuskrip kuno Pesantren Buntet, Jumat, 5 Desember 2025.
Nyai Mamay menunjukkan salah satu manuskrip kuno Pesantren Buntet, Jumat, 5 Desember 2025.Bagi Nyai Mamay Mujahid, keturunan ke-7 pendiri pesantren, salah satu penjaga napas keilmuan Buntet adalah manuskrip. Tersimpan 43 naskah kuno bertarikh sekitar 1800-an, ditulis tangan di atas kertas Eropa dan daluang. Isinya beragam: Al-Quran, Tauhid, Fikih, Nahwu Shorof, hingga Tasawuf.
“Semuanya menggunakan tulis tangan, ini walaupun kita tidak semua manuskrip itu menuliskan muallif-nya, nama penulisnya secara langsung. Sehingga yang paling sulit buat kami untuk melacak siapa penulisnya,” ucap Nyai Mamay.
Sebagian manuskrip diyakini berasal dari catatan santri. Setiap kali mengaji, ilmu yang didapat “diikat” lewat tulisan, menjelma buku yang kini menjadi koleksi berharga pesantren.
Untuk merawatnya, Nyai Mamay mengikuti pelatihan pelestarian naskah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Upaya yang mungkin dilakukan memang terbatas—digitalisasi menjadi pilihan rasional. Namun baginya, menjaga manuskrip tak berhenti pada menyelamatkan kertasnya, melainkan menghidupkan isinya.
“Saya meyakini bahwa Muallif atau para Kyai kita, para penulis kitab ini, itu berharap bahwa apa yang diajarkan, yang ditulis di situ itu bisa terus diajarkan. Bisa terus dipelajari oleh generasi-generasi berikutnya. Nah ini yang paling penting,” imbuhnya kepada Tim Jelajah Pesantren Kompas.com, Jumat (5/12/2026).
Salah satu rujukan penting adalah Kitab Bafadhol Syarah yang disalin sendiri oleh Mbah Muqoyyim—kitab fikih yang masih diajarkan hingga kini.
“Masih diajarkan sampai sekarang. Hampir seluruh kitab-kitab yang ada di kita itu masih diajarkan ke santri-santri. Baik itu Tauhid, Fiqih, Nahwu Shorof, dan lain sebagainya. Yang artinya, kurikulum yang ada pada saat ini, itu sudah diajarkan mulai dari tahun 1700-an di Buntet,” katanya.
Sorogan dan Bandongan: Metode yang Tak Tergantikan
 Kegiatan Bandongan di Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (05/12/2025). Bandongan adalah metode pengajaran di mana kiai membaca kitab dan santri menyimak.
Kegiatan Bandongan di Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (05/12/2025). Bandongan adalah metode pengajaran di mana kiai membaca kitab dan santri menyimak.Tradisi bukan hanya pada kitab, tetapi juga metode. Sorogan dan bandongan tetap menjadi napas pembelajaran.
“Itu masih kita ajarkan melalui metode bandongan dan sorogan, masih kita lakukan sampai sekarang,” ucap Nyai Mamay.
Sorogan—dari kata Jawa sorong—mendorong santri maju membaca kitab di hadapan kiai. Intens, personal, efektif. Bandongan menghadirkan pengajian kolektif; kiai membaca, santri menyimak dan memberi makna pada teks. Keduanya bertahan karena terbukti membentuk kedalaman ilmu.
Tim Kompas.com sempat berkeliling dari satu pondok ke pondok lain yang jumlahnya begitu banyak hingga menyatu dalam satu kawasan seluas desa. Karena areanya sangat luas, tim tidak berjalan kaki, melainkan diantar menggunakan sepeda motor milik para santri.
Pada Jumat malam itu, suasana pesantren terasa sangat hidup. Di setiap sudut rumah dan pondok yang dipisahkan gang-gang kecil, terdengar lantunan pengajian para santri.
Santri dari berbagai usia—anak-anak hingga dewasa, perempuan maupun laki-laki—berkumpul sambil menyodorkan kitab kuning kepada kiai. Mereka mengantre dengan tertib, membaca, lalu mengartikan dan memaknai teks menggunakan bahasa Sunda Cirebonan.
Para santri dan santriwati tampak cekatan membaca kitab kuning, sesekali mendapat bimbingan dari kiai sepuh yang menyimak bacaan mereka.
“Itulah yang disebut metode sorogan,” ujar Muhammad Nurul Alam, salah satu pengajar yang memandu Tim Jelajah Pesantren Kompas.com.
Berbeda dengan sorogan, pada metode lain seorang kiai duduk di depan ratusan santri yang bersila hingga meluber ke halaman pesantren. Sang kiai membaca kitab, mengartikan, lalu menjelaskan maknanya, sementara para santri menyimak dengan saksama.
“Metode ini disebut bandongan. Biasanya cukup lama, dan para santri harus benar-benar menyimak paparan dari kitab kuning tersebut, mulai dari arti hingga maknanya,” kata Alam.
Nilai Lama, Cara Baru: Visi Pesantren di Era Modern
Pengasuh pesantren, KH Muhammad Imaduddin Ishom, menegaskan bahwa kunci daya tahan Buntet ada pada falsafah yang diwariskan para pendahulu:
“Al-Muhafazatu ‘alal qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah wal ‘amalu sholeh,” ucap Kiai Imad, panggilan akrab KH Muhammad Imaduddin Ishom.
Dengan penuh semangat Kiai Imad menyatakan bahwa pesantren yang diasuhnya memiliki tujuan menjaga nilai lama yang baik, mengambil yang baru yang lebih baik, dan terus beramal saleh.
Menurut Kiai Imad, sejak awal Buntet bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga ruang tumbuhnya kesadaran kebangsaan.
Jejak Mbah Muqoyyim dalam menggerakkan santri pada masa perjuangan menjadi fondasi bahwa agama dan cinta tanah air berjalan seiring.
"Di bidang pendidikan, adaptasi terlihat nyata. Selain pendidikan formal, ada kurikulum lokal: Fikih Wanita untuk santri putri, Fikih Sakit di Akademi Keperawatan," tuturnya.
Sekolah-sekolah di bawah yayasan pesantren bahkan menerapkan sistem paperless dan teknologi digital dalam pembelajaran.
“Pesantren tidak alergi modernisasi. Yang kami jaga adalah ruhnya, bukan menolak alatnya,” kira-kira begitu garis sikap yang ia tegaskan.
Lisan, Tulisan, dan Cinta Tanah Air
Bagi Nyai Mamay, Buntet adalah bukti bahwa Islam Indonesia tumbuh bersama sejarah bangsa.
“Itu seperti membuktikan buat saya secara pribadi ya, dan mungkin nanti ini untuk santri-santri juga, bahwa kita adalah bagian dari bangsa ini. Kita tidak terpisahkan dari sejarah bangsa. Kita adalah orang Islam yang Indonesia, sehingga kemudian mencintai negeri ini itu adalah bagian dari iman,” tandasnya.
Di Buntet, tradisi tidak dibekukan. Ia diajarkan, dibacakan, dituliskan, dan kini didigitalisasi. Dari daluang ke layar, dari sorogan ke ruang kelas modern—semuanya bergerak dalam satu garis: menjaga ilmu tetap hidup.
Dan mungkin, di situlah rahasia mengapa pesantren berusia hampir tiga abad ini tetap relevan hari ini.
Sejarah Singkat Pesantren Buntet
Dilansir dari situs resmi Pesantren Buntet, pondok yang kini dikenal sebagai Pesantren Buntet bermula dari inisiatif seorang ulama karismatik, Mbah Muqoyyim, yang memilih meninggalkan jabatan mufti keraton demi mendirikan lembaga pengajaran agama di luar tembok istana.
Catatan sejarah dan tradisi lisan menyebutkan bahwa pondok ini berdiri pada abad ke-18 (sekitar 1750 M), tumbuh dari sebuah langgar sederhana menjadi kampung pesantren yang luas. Pernyataan resmi di situs pesantren dan riset akademik memperkuat tanggalan dan kisah awal berdirinya Buntet.
Baca juga: Gibran ke Pesantren Cipasung Besok, Bawa Misi Santri Melek AI dan Robotik
Kisah hijrah dan penentangan terhadap intervensi kolonial menjadi bagian dari narasi kelahiran Buntet: Mbah Muqoyyim, yang semula berafiliasi dengan struktur kesultanan, memilih jalan mengajar dan mendidik masyarakat luas—sebuah tindakan yang kemudian memberi pondok kekhasan sebagai ruang pendidikan sekaligus mobilisasi sosial.
Penelitian sejarah lokal dan artikel jurnal menyebutkan bagaimana tokoh pendiri ini ikut membentuk sikap kolektif santri terhadap kemerdekaan dan kedaulatan lokal.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang-
![]() Bantah Dukung Pleno PBNU, Pesantren Krapyak Imbau PBNU Hormati Otoritas Kiai Sepuh
Bantah Dukung Pleno PBNU, Pesantren Krapyak Imbau PBNU Hormati Otoritas Kiai Sepuh -
![]() Majelis Masyayikh Rampung Evaluasi 92 Pesantren, Bagaimana Hasilnya?
Majelis Masyayikh Rampung Evaluasi 92 Pesantren, Bagaimana Hasilnya? -
![]() Kemenag–Kemenkop Sepakat Bentuk Koperasi Pesantren dan Masjid
Kemenag–Kemenkop Sepakat Bentuk Koperasi Pesantren dan Masjid -
![]() Forum Bahtsul Masail Pesantren DIY: Syuriyah Tak Berwenang Makzulkan Ketum PBNU
Forum Bahtsul Masail Pesantren DIY: Syuriyah Tak Berwenang Makzulkan Ketum PBNU -
![]() MUI: Dirjen Pesantren Momentum Pesantren Indonesia Naik Kelas di Panggung Global
MUI: Dirjen Pesantren Momentum Pesantren Indonesia Naik Kelas di Panggung Global -
![]() Ribuan Hafizah Berkumpul di Kendal, Menag Ungkap Besarnya Kebutuhan Guru Tahfidz Perempuan di Pesantren
Ribuan Hafizah Berkumpul di Kendal, Menag Ungkap Besarnya Kebutuhan Guru Tahfidz Perempuan di Pesantren -
![]() Pesantren Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang Kini Bersih dari Kayu Gelondongan
Pesantren Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang Kini Bersih dari Kayu Gelondongan